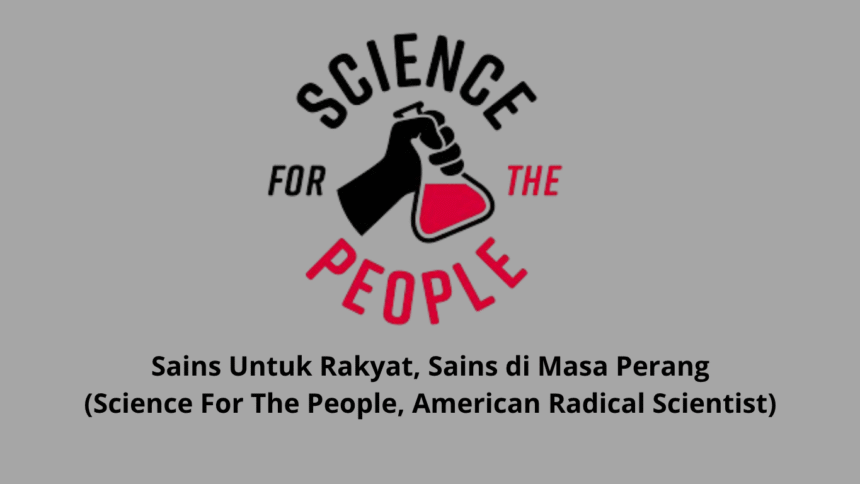Mungkin sejak 2 bulan lalu sampai hari ini, linimasa sosial media penuh dengan riuh kabar kemungkinan Perang Dunia 3. Meski belum ada riset menyeluruh tentang tingkat kebahagiaan manusia pada masa perang, hampir pasti lebih dari setengah populasi manusia di bumi ini membenci peperangan. Tak terkecuali orang-orang cerdas yang pernah hidup di bumi yang biasa kita sebut sebagai Ilmuwan. Jika anda berhasil menamatkan film Oppenheimer, di bagian akhir, ketika Opppenheimer menyesal melihat Bom Atom Little Fat dijatuhkan oleh Militer Amerika di langit Hiroshima-Nagasaki, pastilah kita melihat betapa naif dan ironisnya nasib Oppenheimer di hadapan Presiden Harry S. Truman.
Oppenheimer aktor penting Manhattan Project , tapi ia hanya satu dari ratusan ilmuwan yang terlibat projek ini. Mulanya mereka yang terlibat dalam projek in memiliki motif mirip; bergabung dengan Pasukan Sekutu untuk meruntuhkan Fasisme. Sebagian Ilmuwan , selain memiliki ketakutan bumi akan jauh lebih buruk bila berada di bawah kuasa Hitler, pula mereka mengalami trauma besar hidup di bawah rezim fasis. Tak terkecuali Albert Einstein yang pada tahun 1950an berpindah-pindah ke Ingrris dan Amerika. Nasib buruk bagi Ilmuwan Naif, kalimat ini agaknya tepat disematkan pada Oppenheimer. Ketika ia tahu, Liitle Fat tak jadi jatuh di langit Jerman dan justru di Jepang, ia segera menghadap pada Presiden. Ia merasa bersalah, ia merasa hidupnya dibayang-bayangi darah orang-orang Jepang, ia merasa dihantui kematian orang-orang itu dan ia merasa Amerika mustilah bertanggungjawab. Naasnya, Truman di Kantor Presiden yang melihat Oppenheimer curhat justru mengusirnya. Rasa bersalah Oppenheimer tak layak dan mengejeknya sebagai Ilmuwan Cengeng.
Nasib orang-orang seperti Oppenheimer tak hanya satu, mereka berjumlah lebih dari tiga. Mereka adalah ilmuwan yang kecewa, Sains yang seharusnya menjadi lampu terang masa depan manusia justru berubah menjadi api yang merubah mimpi menjadi abu. Kelak, para penyintas perang ini menularkan kampanye anti-perang pada masa Perang Vietnam. Salah seorang yang terpengaruh dari para sintas ini adalah Charles Schwartz. Awalnya ia hanyalah seorang Mahasiswa Fisika biasa, seperti mahasiswa STEM Indonesia pada umumnya, ia tak bertanya-tanya apakah Sains baik, jika baik untuk apa dan siapa. Tetapi pada tahun 60-an, ia merasa mustahil Ilmuwan tak membuka mata mereka pada gerakan intelektual yang banyak mempertanyakan fungsi Sains untuk masa depan manusia. Secara khusus, ia hidup pada masa mulai banyak penelitian tentang Tekonologi MIliter yang lahir dari penelitian Sains Mutakhir, seperti penelitian tentang atom. Efek Bom Nuklir pada PD II dan pengembangannya pada masa Perang Dingin menarik Schwartz untuk mempertanyakan profesi dan keberpihakannya pada orang banyak, atau secara khusus rakyat Amerika.
Tahun 1967, Schwartz atas keresahan yang ia miliki kemudian membentuk gerakan Science For The People (SftP). Gerakan ini mulanya muncul sebagai bagian dari gelombang massa yang bergerak menuntut Lyndon Johnson agar segera mengakhiri Perang di Vietnam. Kebijakannya yang ingin mempertahankan kawasan Vietnam Selatan sebagai kawasan Independen ia lakukan dalam bentuk mengirim jumlah pasukan Amerika sejumlah 385.000 orang pada tahun 1966. Hadirnya deklarasi Gerakan Anti-Perang Vietnam dan penolakan terhadap Johnson antara lain muncul karena sejak tahun 1955 sampai tahun 19675, Perang Vietnam telah menyebabkan 58.000 Orang Amerika , 3 Juta Orang Vietnam, dan 500.000 orang Kamboja-Laos tewas. Dengan kata lain, gerakan ini tak muncul karena tuntutan masalah Teknologi Perang, pada mulanya.
Bertahun-tahun kemudian, meski harus berhadapan dengan banyak tentangan dari American Association for the Advancement of Science (AAAS) karena dianggap radikal, SftP tetap berdiri hingga kini. Bangunan nilai yang diyakini oleh SftP memang menggangu asosasi profesional ilmu pengetahuan Amerika ini. Pasalnya, Schwartz memberi pernyataan jelas, jika AAAS haruslah membuka mata terhadap setiap kebijakan sains yang justru lebih banyak berkontribusi terhadap Perang, Kesenjangan Ekonomi dan Kekuatan Militer. Pada tahun 1981, SftP kembali dianggap berulah karena telah menerbitkan tiga volume majalah yang kesemuanya bertema, “Militerisasi Sains”. Sebuah tema majalah, yang mengulas pengeluaran anggaran Amerika pada penelitian ilmiah justru lebih banyak dialokasikan untuk pembuatan Teknologi Perang.
Sama seperti pertanyaan yang kerap ditemui oleh Pelajar STEM di Indonesia, apa yang bisa kulakukan sebagai pelajar Sains untuk kepentingan publik? Aku gak ngerti politik, aku gak belajar ilmu sosial, pertanyaan ini pula yang diajukan oleh SftP. Karena itu, Sains Untuk Rakyat, Sains di Masa Perang, adalah Sains yang berhati-hati, Sains yang melibatkan kepentingan orang banyak, Sains yang bisa diakses banyak orang, dan lagi…. Sains yang bisa diukur siapa melakukan apa dan mendapatkan apa. Inilah yang ditanyakan oleh SftP, jika ada pengembangan nuklir buat apa dan untuk siapa, sehingga Sains sebagai alat penerang hidup manusia bisa menjadi lebih demokratis dan tidak hanya untuk kepentingan militer. StfP menyebutnya sebagai, Demokratisasi Sains.
Baca Selengkapnya dalam:
https://scienceforthepeople.org/